Antara Doa, Ngaji Tujuh Hari, dan Tradisi
Pada tulisan "Yang Bapak Tanamkan" Saya kupas bahwa jika seorang meninggal dunia putuslah segala amalnya. Kecuali tiga, yakni ilmu yang bermanfaat, infak sedekah, dan anak yang soleh serta solehah yang selalu mendoakan orang tuanya. Demikian pun tatkala Bapak meninggal, putuslah segala apa yang berhubungan dengan urusan duniawi Bapak, kecuali yang tiga disebutkan di atas.
Hal tersebut saya hubungkan dengan ketika Bapak masih ada mengupas bagaimana jika keluarga membayar paket ngaji tujuh hari tujuh malam di kuburan. Ngaji sebagai doa ketika ada anggota keluarga yang meninggal. Bapak dan saya menolak adat kebiasaan atau tradisi tersebut. Sehingga pada saat nenek (ibu dari bapak) meninggal, Bapak mengganti proyek membayar kelompok yang ngaji tersebut dengan bentuk lain, yang mudah-mudahan bentuk lain itu lebih bermanfaat daripada membayar grup pengaji Al-Quran.
Masih teringat ketika Bapak minta pendapat, "Min, kumaha mun artos cadangan keur ngaos diganti kudipeserkeun korsi?" (Min, bagaimana kalau uang cadangan untuk yang ngaji diganti dengan dibelikan kursi?)
"Saluyu pisan Pa! Urang kudu ngarobah tradisi nu kira-kira salah kaprah." (Setuju sekali Pa! Kita harus mengubah tradisi yang kira-kira salah kaprah) jawab saya.
Pembicaraan saya dan bapak pun akhirnya terjadi waktu Nenek meninggal. Proyek grup ngaji tersebut biayanya secara umum sebesar enam juta rupiah. Bapak membuat keputusan pada keluarga bahwa tidak ada proyek ngaji di kuburan ataupun di rumah. Bapak memutuskan biaya yang umum enam juta itu akan dibelikan kursi untuk kepentingan hajatan atau pengajian di kampung dan akan disimpan atau diserahkan kepada ketua RT setempat. Dengan tujuan, setiap yang hajat dan memerlukan kursi bisa meminjam dari RT. Enam juta rupiah langsung dibelikan kursi dan dapat enam puluh kursi. Lumayan bagi warga yang memerlukan untuk pengajian atau hajatan bisa meminjam secara gratis.
Apa yang Bapak lakukan saat itu, menurut hemat saya sungguh bermanfaat dan bernilai luar biasa! Selama kursi masih digunakan oleh warga atau masyarakat, selama itu pula dipastikan pahala akan terus mengalir baik pada Nenek yang telah meninggal maupun pada Bapak selaku anaknya yang termasuk anak soleh. Kursi akan menjadi amal Nenek juga amal Bapak dan keluarga sekali gus.
Ada beberapa saudara dari keluarga kami juga tetangga yang bertanya, mengapa Nenek tidak diduakan dalam ngaji tersebut. Salah satunya yang bertanya itu adalah Bibi. Saya balik bertanya pada Bibi, "Untuk apa harus membayar ngaji? Kan seharusnya kita yang harus ngaji, sambil mendoakan."
Di luar dugaan, Bibi hanya menjawab, "Gengsi keluarga, Min. "
Waw! Saya hanya terperanjat kaget. Tak ada gunanya membahas lagi masalah ngaji kalau hanya sampai pada masalah gengsi keluarga.
Padahal, jika dikaji ulang masalah proyek ngaji secara kasat mata bingung pahala dan keutamaannya. Ngaji quran dibayar orang lain, bagi yang mengaji entahlah nilainya apa? Lalu, bagi keluarga, apakah dengan mengaji tetapi membayar orang lain kira-kira sama tidak dengan membeli sesuatu, misalnya. Apalagi di kampung halaman harga untuk membayar seolah dipatok secara umum.
Dengan anggota grup mengaji delapan sampai sepuluh orang, ya, saya tidak dapat memungkiri, mungkin ini jalan usaha mereka. Tidak mudah mengaji per satu jam, digilir berikutnya di pukul berapa. Artinya, dalam tempo 24 jam dibagi sepuluh orang, kurang lebih dua koma empat jam (2, 4jam) kebagian mengaji dalam satu hari satu malam, selama tujuh hari. Dengan cara seperti itu anggota grup boleh jadi tidak dapat uaaha atau mencari nafkah yang lain.
Nenek hanya ditahlilkan seperti biasa sampai pada hari ketujuh (tradisi tujuh hari meninggal). Setelah diberi pemahaman oleh Bapak, tentang ngaji diganti kursi, lambat laun keluarga atau warga sekitar yang bertanya menerima apa yang dipaparkan Bapak. Saya apresiasi, tindakan Bapak untuk menghilangkan tradisi proyek ngaji selama tujuh hari adalah tindakan tepat melawan tradisi yang kurang berarti.
Lain dulu ketika Nenek meniggal, lain sekarang saat Bapak meninggal 1 November 2022 lalu. Saya tidak bisa berkutik untuk melawan arus tradisi ngaji. Saya tidak ada yang mendukung. Termasuk dukungan ilmu yang masih mentah tentang agama. Saat Bapak meninggal kelompok yang ngaji itu kalau dulu suka ngaji terus menerus di kuburan selama tujuh hari, naah, sekarang ngajinya di rumah duka.
Sepintas mengapa tidak lagi ngaji di kuburan, jawaban keluarga supaya praktis memberi makan dan minum. Setiap orang dari kelompok ustad tersebut sebagaimana telah disebutkan di atas kebagian ngaji masing-masing satu jam secara bergilir atau muter waktu. Mengaji di tengah rumah dengan tetap tersedia makanan dan minuman, termasuk gula kopi serta termos tempat air panas atau dispenser untuk nyeduh kopi serta rokok. Makan dan minum adalah di luar biaya pokok mengaji. Biaya ngaji yang umum tahun lalu sebesar 12 juta rupiah. Biaya yang cukup pantastis!
Dari apa yang menjadi tradisi, apapun dan bagaimana pun karena tidak mengikat, tetapi memang masih melekat erat di masyarakat, pada akhirnya keluarga dengan suka rela melaksanakan tradisi tersebut. Terlepas apakah pelaksanaan tradisi menjadi gengsi keluarga atau ingin mengeluarkan harta secara iklas. Yang paling utama dari pelaksanaan tradisi tersebut ada kebermanfaatan dan jalinan kebersamaan di antara keluarga dan handai tolan. Semoga!
Bandung Barat, 14 Desember 2023
Catatan/memoar tradisi di kampung halaman


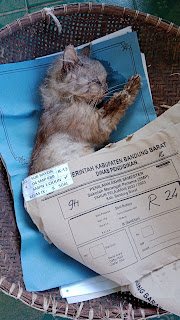

Nah, kalau dihubungkan dengan gengsi keputusan jadi runyam. Tetapi lakukan saja yang terbaik.
BalasHapusTradisi baik tapi memberatkan, mengapa harus dilanjutkan. Seharusnya Bu Mimin berterus terang.
BalasHapusYa Allah, beratnya untuk melawan tradisi yang kurang bermanfaat, tetapi harus ada yang berani.
BalasHapusmenjadi dilema memang, apalagi keluarga belum mendukung. suatu saat memang harus diubah sesuai perintah Bapak. Ie Bapak menarik. suatu saat bisa saya tiru untuk mengubah tradisi tersebut.
BalasHapus